JATIMTIMES - Wafatnya Batoro Katong tidak serta merta mengakhiri stabilitas Kadipaten Ponorogo. Namun di bawah Panembahan Agung, kekuasaan yang diwariskan itu perlahan kehilangan daya kendalinya. Babad mencatat bukan kehancuran yang datang tiba tiba, melainkan erosi kewibawaan yang berlangsung senyap. Disiplin pemerintahan mengendur, loyalitas elite melemah, dan otoritas negara rapuh dari dalam. Pada titik inilah tampak satu pola penting dalam sejarah Jawa. Ketika kekuasaan teritorial merosot, justru terbentuk jaringan genealogis dan spiritual yang kelak memainkan peran jauh lebih menentukan daripada negara itu sendiri.

Transisi Kekuasaan Pasca-Batoro Katong
Baca Juga : Mimpi Menghapus Impunitas Aparat
Sepeninggal Kanjeng Panembahan Batoro Katong, Kadipaten Ponorogo memasuki fase transisi kekuasaan yang krusial. Tahta tidak jatuh ke tangan figur asing, melainkan diwariskan kepada Panembahan Agung, sosok yang dalam tradisi babad dikenal sebagai menantu sekaligus penerus sah dinasti pendiri. Namun kesinambungan genealogis tersebut tidak sepenuhnya berjalan seiring dengan kesinambungan watak dan gaya pemerintahan. Jika masa Batoro Katong ditandai oleh konsolidasi kekuasaan yang keras, disiplin administratif yang ketat, serta keberanian menata negara di tengah konflik terbuka, maka periode Panembahan Agung justru menunjukkan perubahan arah yang lebih lunak, meskipun berdampak luas terhadap stabilitas kadipaten.
Secara kronologis, masa pemerintahan Panembahan Agung diperkirakan berlangsung pada awal abad ke-16, beririsan dengan periode penetrasi kolonial Portugis di Nusantara setelah jatuhnya Malaka pada tahun 1511. Dugaan ini merujuk pada keterkaitan genealogis Panembahan Agung dengan Sunan Pandanaran II, menantu lain Batoro Katong, yang diketahui hidup sekitar tahun 1500. Penempatan kronologi tersebut memperlihatkan bahwa masa transisi kepemimpinan Ponorogo terjadi dalam lanskap geopolitik yang lebih luas, ketika jaringan perdagangan, dakwah Islam, dan pengaruh kolonial Eropa mulai membentuk dinamika baru di kawasan Asia Tenggara.
Babad Ponorogo mencatat Panembahan Agung sebagai figur yang memiliki hati dan budi berbeda dari pendahulunya. Ia digambarkan lebih lunak wataknya, cenderung menghindari konfrontasi langsung, dan kurang tegas dalam mengambil keputusan strategis. Ketegasan administratif yang menjadi ciri utama pemerintahan Batoro Katong perlahan mengendur. Pengawasan terhadap wilayah luar kota melemah, disiplin aparat longgar, dan intensitas relasi antara pusat kadipaten dengan para demang desa tidak lagi terjaga secara ketat. Negara tidak runtuh secara dramatis, tetapi mengalami erosi kewibawaan yang berlangsung perlahan dan nyaris tak kasatmata.
Perubahan ini menjadi kontras tajam bila dibandingkan dengan watak negara yang dibangun Batoro Katong pada fase awal berdirinya Ponorogo. Sebagai putra Dyah Kertawijaya atau Brawijaya V, raja Majapahit akhir yang memerintah di tengah krisis besar, Raden Katong datang ke Wengker bukan sebagai penguasa pasif. Ia membawa mandat politik dari Demak, legitimasi darah Majapahit, serta kesadaran penuh bahwa pedalaman Jawa Timur hanya dapat ditundukkan melalui kombinasi kekerasan terukur, simbol keagamaan, dan rekayasa sosial yang cermat. Negara Ponorogo lahir bukan dari kesepakatan damai, melainkan dari pertarungan panjang melawan elite lama, terutama figur Ki Ageng Kutu yang merepresentasikan dunia pra negara dengan basis kesaktian personal dan patronase warok.
Pada masa Batoro Katong, kekuasaan ditegakkan melalui struktur yang jelas. Kota dibangun sebagai benteng, sungai difungsikan sebagai batas pertahanan, jembatan ditutup setiap malam, dan aparat ditempatkan hingga ke wilayah pedesaan. Empat puluh keluarga dari Demak dipindahkan sebagai inti masyarakat negara, disusul migrasi penduduk dari Bagelen dan dusun sekitar. Pertanian ditata sebagai fondasi ekonomi, sementara keluarga penguasa dijadikan tulang punggung administrasi dengan menempatkan kerabat dan keturunan pada jabatan strategis. Dalam babad, fase ini digambarkan sebagai masa murah sandang dan pangan, sebuah formula klasik legitimasi Jawa yang menandai hadirnya wahyu kekuasaan.
Dalam kerangka inilah suksesi kepada Panembahan Agung menjadi titik balik. Negara yang dibangun melalui disiplin keras dan ketegangan kosmologis tiba tiba berada di tangan penguasa yang lebih mengandalkan kelunakan budi dan kompromi personal. Babad tidak mencatat adanya pemberontakan besar pada awal pemerintahannya, tetapi justru menunjukkan gejala yang lebih berbahaya bagi negara Jawa pra modern, yakni pudarnya rasa takut dan hormat. Banyak demang di wilayah luar kota mulai jarang sowan. Hubungan patronase melemah. Pengelolaan pertanian tidak lagi terpantau secara intensif. Negara tetap berdiri secara formal, tetapi kehilangan daya kendali simbolik dan administratif.
Dengan demikian, masa pemerintahan Panembahan Agung dapat dibaca sebagai fase transisi dari negara pendiri yang keras menuju negara dinasti yang mulai mengandalkan legitimasi warisan semata. Ia mewarisi struktur yang dibangun Batoro Katong, tetapi tidak sepenuhnya mewarisi energi politik yang menopangnya. Dalam konteks sejarah Jawa, kondisi semacam ini sering kali menjadi celah bagi munculnya konflik laten, dendam genealogis, dan perebutan pengaruh di tingkat elite lokal. Ponorogo pada masa ini tidak hancur, tetapi mulai rapuh dari dalam, membuka jalan bagi dinamika berikutnya yang kelak menentukan arah sejarah kadipaten.

Di Antara Babad dan Silsilah: Perdebatan Identitas Panembahan Agung Ponorogo
Asal usul Panembahan Agung menempati posisi krusial dalam tradisi historiografi Ponorogo karena pada titik inilah persoalan genealogi, legitimasi religius, dan arah politik pasca pendirian kadipaten saling bertemu. Babad Ponorogo menyebut Panembahan Agung sebagai putra Batoro Katong, sebuah keterangan yang secara lahiriah tampak sederhana dan administratif. Namun ketika data babad dibaca berdampingan dengan tradisi silsilah keluarga, naskah genealogis, serta kajian modern, gambaran tentang posisi Panembahan Agung menjadi jauh lebih kompleks.
Tradisi Sarasilah Gandalayan menyebut bahwa Batoro Katong memiliki enam orang anak yang kemudian membentuk jaringan politik dan religius lintas wilayah. Anak pertama adalah Panembahan Pembayun yang dalam sejumlah catatan disebut sebagai penerus kekuasaan Ponorogo setelah wafatnya Batoro Katong. Dalam tradisi Kusumatjitra, Panembahan Pembayun dipandang sebagai adipati yang secara administratif menggantikan kedudukan ayahnya. Dari garis keturunannya inilah muncul figur Panembahan Agung I, yang sering disamakan atau tertukar identitasnya dengan Panembahan Agung lain dalam silsilah Ponorogo.
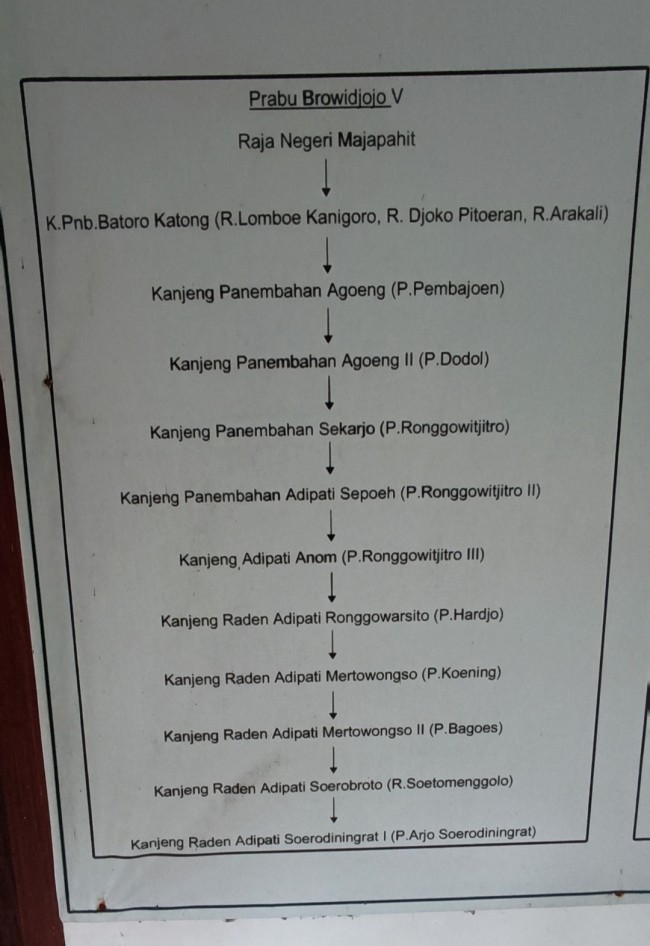
Anak kedua adalah Kanjeng Panembahan Bathara yang disebut berkuasa di Kaliwungu. Tokoh ini menunjukkan adanya ekspansi jaringan keluarga Ponorogo ke wilayah pesisir utara Jawa yang pada abad ke 16 menjadi jalur penting perdagangan dan dakwah Islam. Keberadaan cabang Kaliwungu menegaskan bahwa keluarga Batoro Katong tidak hanya berorientasi pada kekuasaan pedalaman, tetapi juga membangun hubungan dengan kawasan pesisir yang terhubung dengan jaringan ulama dan saudagar Muslim.
Anak ketiga adalah Kanjeng Ratu Agung yang dalam tradisi silsilah disebut menjadi garwa Sultan Demak. Meskipun sumber primer tidak menyebut secara pasti Sultan Demak yang dimaksud, tradisi genealogis ini menunjukkan adanya aliansi perkawinan antara Ponorogo dan pusat kekuasaan Islam pesisir. Hubungan tersebut memperkuat legitimasi religius Batoro Katong sebagai penguasa dakwah sekaligus memperlihatkan strategi politik melalui perkawinan elite pada masa awal penyebaran Islam di Jawa.
Anak keempat adalah Kanjeng Panembahan Agung yang dalam tradisi Sarasilah disebut memiliki empat orang anak perempuan, yaitu Raden Ayu Pembayun yang menikah dengan Kanjeng Panembahan Agung I, Raden Ayu Panembahan yang menikah dengan Panembahan Agung di Kajoran, Raden Ayu Adji Mustopo, serta Raden Ayu Pangulu Ageng. Melalui garis inilah jaringan genealogis Kajoran berkembang menjadi salah satu poros spiritual dan politik penting dalam sejarah Jawa. Dalam kajian H. J. de Graaf tentang masalah Kajoran disebut bahwa tokoh yang dikenal sebagai Panembahan Agung Kajoran kemungkinan identik dengan figur yang memiliki berbagai gelar seperti Pangeran Kajoran I, Sayyid Kalkum, Pangeran Wotgaleh, dan Panembahan Mas Kajoran.
Anak kelima adalah Kiai Ageng Panembahan Ronggo yang dalam beberapa tradisi lokal dikaitkan dengan peran spiritual dan kepemimpinan religius. Meskipun data tentang tokoh ini tidak sebanyak saudara saudaranya, keberadaannya menunjukkan kesinambungan tradisi kepemimpinan ulama dalam keluarga Batoro Katong.
Anak keenam adalah Raden Ayu Sumendi yang disebut menikah dengan Pangeran Sumendi. Perkawinan ini memperlihatkan pola aliansi horizontal di kalangan elite lokal Jawa yang memperluas jaringan kekuasaan keluarga Ponorogo ke wilayah lain.
Keragaman jalur keturunan tersebut menjadi salah satu sebab munculnya kebingungan historiografis mengenai identitas Panembahan Agung. Sarasilah Gandalayan bahkan mencatat adanya tiga tokoh berbeda yang menggunakan nama Panembahan Agung. Pertama adalah Panembahan Agung I yang merupakan putra Panembahan Pembayun. Kedua adalah Panembahan Agung yang disebut sebagai putra langsung Batoro Katong. Ketiga adalah Panembahan Agung Kajoran yang merupakan menantu dari Panembahan Agung generasi sebelumnya. Tumpang tindih nama dan gelar ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Jawa, nama kebesaran sering diwariskan sebagai simbol legitimasi spiritual dan politik, bukan sekadar identitas personal.
Perdebatan mengenai siapa sebenarnya Panembahan Agung semakin kompleks ketika sumber babad dibandingkan dengan kajian modern. Purwowijoyo dan Kartasiswaya menegaskan bahwa Panembahan Agung adalah pengganti langsung Batoro Katong. Namun Ong Hok Ham menyebut bahwa tokoh yang menggantikan Batoro Katong kemungkinan menggunakan nama lain yaitu Pangeran Waliyullah. Sementara itu Kusumatjitra menyatakan bahwa pengganti awal Batoro Katong adalah Panembahan Pembayun dan bahwa Panembahan Agung merupakan cucu Batoro Katong melalui tokoh Pangeran Dodol.
Di tengah perdebatan genealogis tersebut muncul bukti penting berupa karya intelektual yang dikaitkan dengan Panembahan Agung, yaitu Serat Panitibaya. Dalam bagian pembuka naskah ini disebut bahwa pengarangnya adalah Panembahan Agung, putra Batoro Katong, penguasa Ponorogo pada masa yang berdekatan dengan Sunan Giri. Serat Panitibaya berisi seratus tujuh puluh enam ajaran etika kehidupan yang menggambarkan konsep moralitas penguasa Jawa Islam awal.
Keberadaan Serat Panitibaya juga didukung oleh banyak salinan naskah yang tersebar di berbagai pusat dokumentasi Jawa. Naskah ini tercatat disalin kembali oleh R. Tanaya pada 1851 tahun Jawa dan disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. Salinan lain tersimpan di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, Museum Radya Pustaka, serta Reksa Pustaka Mangkunegaran. Nancy K. Florida juga mencatat keberadaan salinan naskah tersebut dalam katalog manuskrip Surakarta yang menunjukkan bahwa teks ini memiliki sirkulasi intelektual luas di lingkungan keraton Jawa.
Banyaknya versi silsilah dan keberagaman naskah menunjukkan bahwa figur Panembahan Agung bukan sekadar tokoh administratif penerus kadipaten, melainkan simpul penting dalam jaringan genealogis, spiritual, dan intelektual Jawa. Oleh karena itu identifikasi tokoh ini menuntut penelitian yang teliti dengan membandingkan sumber babad, naskah silsilah keluarga, manuskrip sastra, serta kajian historiografi modern.

Asal Usul Panembahan Agung dalam Catatan Wangsa Kajoran
Namun, ketika sumber babad tersebut dibaca berdampingan dengan tradisi genealogis ulama Jawa Timur serta catatan mengenai jaringan Wali Songo, muncul lapisan makna yang lebih kompleks. Dalam silsilah wangsa Kajoran, Panembahan Agung dikaitkan dengan Sunan Ampel melalui jalur ayahnya yang disebut sebagai Pangeran Tumapel, yang dalam tradisi tersebut dikenal sebagai putra Sunan Ampel dari Surabaya. Versi ini menempatkan Panembahan Agung bukan sekadar sebagai pejabat lokal hasil perkawinan politik, melainkan sebagai figur penghubung antara elite dakwah Islam awal dengan kekuasaan pedalaman Ponorogo.
Dalam versi wangsa Kajoran, Panembahan Agung disebut sebagai cucu Sunan Ampel yang kemudian menikah dengan putri Batoro Katong. Perkawinan tersebut tidak dapat dibaca sebagai peristiwa domestik semata, melainkan sebagai tindakan politik dan ideologis yang menyatukan dua garis legitimasi sekaligus. Di satu sisi terdapat Batoro Katong sebagai anak Majapahit, pewaris darah rajawi Hindu Buddha yang telah bertransformasi menjadi penguasa Islam pedalaman. Di sisi lain terdapat trah Sunan Ampel, pusat otoritas religius Islam Jawa yang memiliki legitimasi spiritual paling kuat pada abad ke lima belas. Penyatuan kedua garis ini menjadikan Panembahan Agung figur ideal untuk menjembatani negara dan dakwah, pedalaman dan pesisir, dunia lama dan dunia baru.
Perbedaan narasi mengenai asal usul Panembahan Agung tidak dapat dilepaskan dari satu simpul genealogis penting dalam sejarah Jawa, yakni Wangsa Kajoran. Kajoran merupakan wilayah agraris subur di selatan Klaten yang dalam simbolisme Jawa sering dimaknai sebagai kejora atau bintang timur, lambang cahaya penuntun dan awal kebangkitan. Dari wilayah inilah tumbuh sebuah wangsa religio politik yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Mataram Islam. Tradisi Kajoran tidak hanya memelihara garis darah, tetapi juga memproduksi otoritas spiritual yang menyatu dengan kekuasaan politik, sebuah pola yang akan menjadi ciri khas negara Islam Jawa pedalaman.
Secara genealogis menurut catatan ini, Sunan Ampel menikah dengan putri Ki Wirajaya atau Ki Kembang Kuning, tokoh lokal Surabaya yang memiliki pengaruh kuat di wilayah pesisir timur. Dari perkawinan ini lahir Pangeran Tumapel yang dalam sejumlah tradisi juga dikenal sebagai Syekh Hambyah. Pangeran Tumapel kemudian menurunkan dua figur penting yang menjadi poros penyebaran Islam di pedalaman Jawa. Yang pertama adalah Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat, tokoh kunci dalam islamisasi kawasan selatan Jawa Tengah dan pendiri pusat spiritual Tembayat. Yang kedua adalah Sayid Kalkum, yang dalam berbagai sumber dikenal pula dengan nama Pangeran ing Wot Galeh, Panembahan Agung Ponorogo, atau Adipati Ponorogo kedua. Sayid Kalkum inilah yang disebut menikah dengan putri Batoro Katong dan kemudian menggantikan mertuanya sebagai penguasa Ponorogo.
Dengan demikian menurut catatan wangsa Kajoran, Panembahan Agung sebagai Adipati kedua Ponorogo tidak hanya menantu Batoro Katong, melainkan juga cucu buyut Sunan Ampel. Posisi ini menjadikannya simpul genealogis yang sangat strategis karena menghubungkan langsung kekuasaan lokal Ponorogo dengan jaringan Wali Songo. Dalam konteks Jawa abad ke lima belas, nasab semacam ini memiliki bobot politik yang jauh melampaui kecakapan administratif atau kemampuan militer. Legitimasi penguasa ditentukan bukan hanya oleh penguasaan wilayah, tetapi oleh kedekatannya dengan sumber wahyu dan otoritas religius.
Dengan menganalisis catatan genealogis Kajoran, penulis berpendapat bahwa pilihan Batoro Katong terhadap Panembahan Agung sebagai penerus menjadi masuk akal ketika dibaca dalam kerangka misi awal pendirian Ponorogo.Jika Ponorogo akhir abad kelima belas tidak dibaca sebagai negara administratif modern, melainkan sebagai medan transisi ideologi, maka jelas bahwa tujuan utama Batoro Katong bukan sekadar memperluas kekuasaan teritorial. Wengker merupakan basis budaya warok yang kuat dalam tradisi pra Islam, memiliki kosmologi sendiri, dan sejak lama menjadi wilayah dengan otonomi kultural yang keras. Penaklukan Wengker bukan hanya operasi militer, melainkan operasi kultural religius untuk menanamkan Islam sebagai ideologi negara. Dalam konteks ini, misi Batoro Katong sepenuhnya sejalan dengan proyek Wali Songo, yakni islamisasi Jawa melalui pembentukan negara, bukan sekadar dakwah individual.

Penulis memandang dukungan Raden Patah dan para wali kepada Batoro Katong pada awal pemerintahannya tidak dapat dibaca sekadar sebagai ornamen cerita babad. Pada masa itu, wali merupakan sumber legitimasi tertinggi; penguasa tanpa restu mereka adalah penguasa rapuh yang mudah digugat, baik secara politik maupun spiritual. Sokongan Sunan Ampel dan jaringan wali menandai bahwa Batoro Katong menjalankan mandat dakwah yang dilembagakan melalui kekuasaan. Penaklukan Wengker dibingkai sebagai jihad kultural, sementara proses islamisasi dilekatkan ke dalam struktur negara. Sejak awal, Kadipaten Ponorogo berdiri bukan sebagai kerajaan netral, melainkan sebagai negara dakwah.
Di titik inilah posisi Sunan Ampel menjadi kunci. Sunan Ampel bukan sekadar ulama besar, melainkan jembatan darah antara Majapahit dan Islam. Ia adalah putra Dewi Candra Wulan dari Kerajaan Champa, adik Ratu Dwarawati, permaisuri Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya. Dengan demikian, Sunan Ampel adalah keponakan langsung Brawijaya V. Fakta ini menjadikannya figur yang sah secara darah Majapahit sekaligus sah secara spiritual Islam. Tidak ada tokoh lain di Jawa pada masa itu yang memiliki modal legitimasi sekuat ini. Ia diterima oleh elite lama Majapahit yang sedang runtuh dan sekaligus menjadi pusat otoritas Islam baru yang sedang bangkit.
Dalam kerangka inilah keputusan Batoro Katong memilih menantu dari trah Sunan Ampel tidak dapat dibaca sebagai kebetulan, apalagi kelemahan politik. Ia adalah langkah strategis terakhir dalam proses islamisasi kekuasaan. Batoro Katong memastikan bahwa Ponorogo tidak kembali ke pola lama, bahwa negara tetap berada dalam orbit wali, dan bahwa dakwah tidak berhenti pada generasi pertama. Dengan menyerahkan kekuasaan kepada figur yang kuat secara nasab religius, Batoro Katong menyerahkan arah sejarah Ponorogo kepada jaringan Wali Songo. Ia membangun negara, tetapi tidak mengklaim masa depannya sebagai milik pribadi atau dinasti darahnya sendiri.
Konsekuensi dari pilihan ini memang jelas terlihat. Di bawah Panembahan Agung dan keturunannya, disiplin administratif melemah dan wibawa teritorial Ponorogo perlahan menurun. Namun kemunduran ini bukan kegagalan personal semata, melainkan harga sejarah dari sebuah pilihan sadar. Fokus utama Panembahan Agung bukan pada penguatan militer atau birokrasi, melainkan pada pemeliharaan kesucian nasab, perawatan jaringan spiritual, dan penyebaran pengaruh kultural. Negara melemah, tetapi tradisi menang. Kekuasaan surut, tetapi pengaruh spiritual justru menyebar luas.
Dari rahim Ponorogo inilah kemudian lahir Wangsa Kajoran, Sunan Kajoran, dan simpul genealogis yang kelak menopang Pajang dan Mataram Islam. Dalam perspektif jangka panjang, pilihan Batoro Katong terbukti berhasil. Ponorogo mungkin tidak tampil sebagai kekuatan besar dalam peta politik Jawa, tetapi ia menjadi fondasi sunyi dari islamisasi pedalaman. Batoro Katong bukan gagal membangun negara. Ia berhasil menanamkan Islam dalam struktur kekuasaan Jawa, meskipun harus mengorbankan kekuatan teritorial Ponorogo itu sendiri.
Sampai pada titik ini, jelas bahwa kisah Panembahan Agung tidak dapat dibaca semata sebagai sejarah lokal Ponorogo. Ia adalah simpul peralihan antara negara pendiri, jaringan wali, dan pembentukan elite Jawa pedalaman. Bab bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana kemunduran negara justru menjadi rahim bagi bangkitnya wangsa yang kelak menentukan sejarah Pajang, Mataram, dan Surakarta.

Pemerintahan Longgar dan Pudarnya Loyalitas Elite
Dalam memimpin Ponorogo, Panembahan Agung memang berupaya melanjutkan apa yang telah dirintis Batoro Katong, tetapi tanpa disiplin kekuasaan yang kuat. Pemerintahan dijalankan dengan longgar, urusan kadipaten kurang mendapat perhatian utama, dan relasi dengan elite lokal tidak lagi terjaga secara intens. Akibatnya segera terasa. Banyak demang di wilayah luar kota enggan sowan, sektor pertanian melemah, pengelolaan desa tidak terpantau, dan wibawa Kadipaten Ponorogo perlahan merosot.
Dalam konteks melemahnya otoritas ini, Surahandaka membaca peluang. Ia bukan sekadar pejabat daerah, melainkan figur yang menyimpan dendam genealogis dan politis. Surahandaka dan Suramenggala diketahui sebagai putra Ki Demang Suryangalan atau Ki Ageng Kutu, tokoh lama yang kekuasaannya ditumbangkan pada masa Batoro Katong. Keduanya kemudian masuk ke lingkungan Katongan dan bahkan menjadi bagian dari lingkar keluarga melalui hubungan ipar dengan Batoro Katong.

Dua Saudara, Dua Jalan Politik
Baca Juga : Kabupaten Malang Diproyeksikan Mendapat Program Hilirisasi Kelapa
Setelah dewasa, jalan hidup keduanya berbelah. Suramenggala diangkat menjadi Demang Wonokerto (kini wilayah Kertosari) dan dipercaya sebagai pengawal pribadi Bathoro Katong, lalu tetap menjadi pilar keamanan Ponorogo setelah sang adipati wafat. Sementara itu, Surahandaka diangkat menjadi Demang Surukubeng, menggantikan kedudukan ayahnya. Secara formal ia berada dalam struktur kadipaten, tetapi secara batin menyimpan luka lama.
Ketika Surahandaka melihat pemerintahan Panembahan Agung semakin melemah, kegembiraannya bercampur dengan hasrat balas dendam. Namun seluruh upaya itu selalu kandas. Penyebabnya satu, Suramenggala. Ia tampil sebagai figur kunci penjaga stabilitas Ponorogo, sosok perantara sejarah yang paradoksal, berdarah lawan tetapi justru menjadi benteng negara. Dalam tradisi lisan dan babad, ia dikenang sebagai warok penjaga negara.

Adipati Anom (Pangeran Dodol) dan Erosi Kekuasaan Negara
Babad Ponorogo mencatat Panembahan Agung memiliki empat orang putra. Ketika wibawa Kadipaten Ponorogo kian merosot, kekuasaan diserahkan kepada putra sulungnya, Adipati Anom atau Pangeran Dodol. Proses ini berlangsung bukan sebagai langkah darurat, melainkan sebagai bagian dari mekanisme suksesi bangsawan yang telah mapan dalam tradisi keluarga Katongan.
Pangeran Dodol merupakan putra kandung Panembahan Agung. Secara genealogis, ia adalah cucu Panembahan Batoro Katong yang menjadi fondasi awal Kadipaten Ponorogo pasca runtuhnya hegemoni Majapahit. Dengan demikian, Pangeran Dodol adalah Adipati Ponorogo ketiga dari garis darah Katongan, yang menandai kesinambungan dinasti lokal sekaligus kesinambungan misi politik dan keagamaan yang dirintis generasi sebelumnya.
Sebagai anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan dan pendiri kadipaten, Pangeran Dodol dibesarkan dalam tata kehidupan istana yang sarat dengan sistem, etika, dan tata cara pemerintahan. Dalam tradisi kerajaan Jawa, putra mahkota tidak sekadar menjadi ahli waris biologis, tetapi juga subjek kaderisasi kekuasaan yang ketat. Sejak usia dini, calon penguasa dipersiapkan melalui pendidikan politik, penguasaan adat, serta pengenalan langsung pada urusan pemerintahan. Oleh karena itu, ketika estafet kekuasaan berpindah, seorang putra mahkota dituntut siap atau tidak siap untuk memikul amanah kepemimpinan.
Pangeran Dodol menyadari sepenuhnya posisi tersebut. Ia mengasah pengetahuan pemerintahan secara langsung di bawah bimbingan ayahnya, Panembahan Agung. Sang ayah memahami bahwa keberlanjutan Kadipaten Ponorogo bergantung pada kualitas penerusnya. Harapan besar diletakkan pada Pangeran Dodol agar mampu memimpin lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Setelah memasuki usia dewasa, Pangeran Dodol secara resmi menggantikan kedudukan ayahnya dan memperoleh gelar baru sebagai Pangeran Adipati Anom.
Pada masa pemerintahannya, jabatan patih dipegang oleh Kyai Wurat, putra dari Patih Seloadji. Dengan demikian, struktur pemerintahan Kadipaten Ponorogo pada periode ini masih berada dalam satu jaringan trah yang saling terkait antara garis Batoro Katong dan keluarga patih. Harmonisasi pemerintahan dibangun atas pembagian tugas dan fungsi yang relatif jelas antara adipati dan pejabat istana. Pola ini pada awalnya menciptakan stabilitas internal dan menjaga keutuhan sosial masyarakat Ponorogo.
Namun harmonisasi tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki masa pemerintahan Pangeran Adipati Anom, pengaruh ekspansi politik dari luar kadipaten semakin kuat. Menurut pandangan Purwowijoyo, pada era Pangeran Dodol jalannya pemerintahan semakin melemah dan kehidupan pertanian mengalami kemunduran. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari situasi hegemoni antardaerah yang saling berebut pengaruh. Tarik menarik kekuasaan antara wilayah yang berusaha mempertahankan otonomi dan kekuatan politik yang tengah bangkit menciptakan tekanan struktural yang berat bagi kadipaten yang relatif muda seperti Ponorogo.
Pangeran Dodol menjabat sebagai Adipati Ponorogo sekitar tahun 1586-1601, bertepatan dengan masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama. Pemerintahan Mataram pada periode ini ditandai oleh rangkaian peperangan dan pemberontakan. Kerajaan yang berpusat di Kotagede terus melakukan ekspansi untuk menundukkan para bupati yang berupaya melepaskan diri, termasuk Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan, dan Demak. Satu per satu wilayah tersebut akhirnya dapat dikuasai, dengan Surabaya sebagai daerah terakhir yang ditundukkan melalui dukungan Sunan Giri.
Sebagaimana daerah lain, Ponorogo tidak luput dari dampak konflik tersebut dan akhirnya masuk ke dalam lingkup kekuasaan Mataram. Dalam konteks ini, peperangan dan ketidakstabilan politik hampir pasti membawa kemunduran di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi. Pertanian sebagai sektor fundamental sangat menentukan ketahanan sosial. Gagalnya sektor ini akan berdampak langsung pada kemiskinan, kesehatan, dan rapuhnya sendi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Situasi ini menjadi semakin berat mengingat Kadipaten Ponorogo masih tergolong baru dan telah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Sebagai kadipaten yang sedang membangun tata kelola, Ponorogo membutuhkan stabilitas dan manajemen pemerintahan yang kuat untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi tersebut, upaya Pangeran Dodol untuk menyejahterakan masyarakat menghadapi berbagai kendala struktural dan politik yang berada di luar kendali pribadinya.
Meski demikian, berbagai daya dan upaya tetap dicurahkan oleh Pangeran Adipati Anom demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, Pangeran Dodol dimakamkan di pemakaman keluarga Trah Katongan di Desa Setana, Ponorogo, tepat di sisi kanan makam kakeknya, Panembahan Batoro Katong. Estafet kepemimpinan Kadipaten Ponorogo kemudian diteruskan oleh putranya, Pangeran Sedakarya, yang melanjutkan perjalanan sejarah kadipaten dalam lanskap politik Jawa yang semakin kompleks.

Runtuhnya Negara dan Lahirnya Wangsa Kajoran
Di luar pusaran kemunduran politik Kadipaten Ponorogo, dari garis Panembahan Agung justru tumbuh satu wangsa yang kelak memainkan peran jauh lebih besar dalam sejarah Jawa, yakni Wangsa Kajoran. Jika Ponorogo sebagai negara teritorial mengalami pelapukan kekuasaan, maka melalui jalur darah dan spiritualitas, keturunannya justru menyebar dan mengakar di pusat pusat kekuasaan Jawa pedalaman.
Selain Pangeran Dodol, dari pernikahan Panembahan Agung dengan putri Batoro Katong lahir pula Pangeran Maulana Mas, tokoh yang kelak dikenal sebagai Panembahan Agung Kajoran atau Sunan Kajoran.

Berbeda dengan ayahnya yang terikat pada urusan pemerintahan kadipaten, Pangeran Maulana Mas memilih jalan spiritual dan kultural. Ia berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon dan kemudian menetap di wilayah Kajoran, sebuah kawasan agraris di selatan Klaten yang secara simbolik dimaknai sebagai kejora atau bintang penuntun. Di tempat inilah ia membangun pusat spiritual yang kelak menjadi simpul penting jaringan ulama dan bangsawan Jawa.
Panembahan Agung Kajoran memperkuat posisinya melalui perkawinan politik strategis. Ia menikah dengan dua putri Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat, saudara kandung Panembahan Agung Ponorogo. Perkawinan ini mengikat Ponorogo, Tembayat, Pajang, dan Mataram dalam satu simpul genealogis yang kokoh. Dari pernikahan tersebut lahir anak anak yang kelak menjadi poros penting dalam sejarah politik Jawa.
Salah satu putrinya adalah Raden Ayu Kajoran, yang dipersunting oleh Panembahan Senapati, pendiri Mataram Islam. Perkawinan ini bukan sekadar ikatan keluarga, melainkan aliansi ideologis antara kekuatan spiritual Kajoran dan negara baru Mataram. Dari rahim Raden Ayu Kajoran lahir keturunan yang menguasai wilayah strategis seperti Ponorogo dan Madiun, sekaligus menjadi penopang legitimasi dinasti Mataram awal.
Selain Raden Ayu Kajoran, Sunan Kajoran juga memiliki putri bernama Raden Ayu Sindusena, yang menikah dengan Pangeran Sindusena, putra Sultan Hadiwijaya Pajang. Putri lainnya, Raden Ayu Panembahan Timur, dipersunting Panembahan Timur, Adipati Madiun. Sementara putranya, Raden Suroso atau Pangeran Agus, menikah dengan Roro Subur, putri Ki Ageng Pemanahan. Melalui jaringan perkawinan ini, Wangsa Kajoran menancapkan pengaruhnya di Pajang, Mataram, Ponorogo, dan Madiun, menjadikannya wangsa lintas wilayah dan lintas generasi.
Dari garis Raden Ayu Kajoran dan Panembahan Senapati lahir Pangeran Jayaraga, tokoh sentral dalam konflik internal Mataram pada awal abad ketujuh belas. Jayaraga adalah pangeran berdarah ganda, keturunan langsung pendiri Mataram sekaligus cucu Sunan Kajoran. Ia memerintah sebagai adipati Gadingrejo di Ponorogo selatan dan memiliki legitimasi lokal yang sangat kuat. Namun legitimasi inilah yang kemudian menumbuhkan ambisi, hingga ia memberontak terhadap Panembahan Hanyakrawati pada sekitar tahun 1608. Pemberontakan ini berakhir dengan pembuangan Jayaraga ke wilayah Nusa Kambangan, menandai rapuhnya fondasi politik Mataram awal.
Dari jalur lain, yakni keturunan Raden Suroso atau Pangeran Agus, Wangsa Kajoran terus berkembang. Raden Suroso, putra Panembahan Agung Kajoran, menikah dengan Roro Subur, putri Ki Ageng Pemanahan, dan menurunkan Pangeran Raden ing Kajoran. Pangeran Raden ing Kajoran kemudian menikah dengan Raden Ayu Wangsa Cipta, putri Panembahan Senapati Mataram. Dari perkawinan inilah lahir sejumlah tokoh penting Wangsa Kajoran, termasuk Panembahan Rama ing Kajoran, figur sentral yang kelak menjadi poros ideologis perlawanan terhadap Mataram dalam Perang Trunajaya pada paruh akhir abad ketujuh belas.
Panembahan Rama bukan sekadar bangsawan pinggiran. Ia adalah cicit Panembahan Agung Kajoran, keturunan Sunan Ampel, Sunan Tembayat, Batoro Katong, dan Panembahan Senapati. Dalam dirinya berhimpun legitimasi wali, bangsawan pedalaman, dan pendiri negara Mataram. Ketika Amangkurat I menjalankan pemerintahan absolut yang meminggirkan ulama dan bangsawan lama, Panembahan Rama tampil sebagai poros oposisi ideologis.
Ia menjadikan Trunajaya sebagai menantu dan memasukkannya ke dalam jaringan Kajoran. Dengan demikian, Perang Trunajaya yang mencapai puncaknya pada keruntuhan istana Plered tahun 1677 tidak dapat dipahami semata sebagai pemberontakan Madura terhadap Mataram, melainkan sebagai konflik internal keluarga besar elite Jawa, dengan Wangsa Kajoran berperan sebagai pemberi legitimasi moral dan spiritual. Panembahan Rama sendiri tidak tampil di medan perang, tetapi berfungsi sebagai arsitek ideologis perlawanan terhadap istana.

Ironi sejarah mencapai puncaknya ketika darah Wangsa Kajoran justru kembali menduduki singgasana Jawa. Jalur ini bermula dari Panembahan Agung Kajoran atau Sunan Kajoran, buyut Sunan Ampel, yang menikah dengan putri Sunan Tembayat. Dari perkawinan itu lahir Raden Suroso atau Pangeran Agus, yang kemudian menikah dengan Roro Subur, putri Ki Ageng Pemanahan. Dari pasangan inilah lahir Pangeran Raden ing Kajoran.
Pangeran Raden ing Kajoran menikah dengan Raden Ayu Wangsa Cipta, putri Panembahan Senapati Mataram. Perkawinan ini menjadi simpul penting yang mengikat darah wali Kajoran dengan wangsa raja Mataram awal. Dari pasangan tersebut lahir Raden Ayu Panembahan Raden. Ia kemudian menikah dengan Panembahan Raden, putra Pangeran Mas, cucu Pangeran Benowo Pajang, sehingga memperluas jejaring genealogisnya hingga ke trah Pajang.
Dari perkawinan Raden Ayu Panembahan Raden inilah lahir Kangjeng Ratu Wetan, yang lebih dikenal sebagai Ratu Mas Labuhan atau Ratu Mas Pelabuhan. Ia menjadi permaisuri kedua Susuhunan Amangkurat I. Dari rahim Ratu Mas Labuhan lahir Pangeran Puger, yang kelak naik takhta sebagai Susuhunan Pakubuwana I, pendiri Dinasti Surakarta. Ratu Mas Labuhan sendiri setelah wafat dimakamkan di Plered, di sisi barat Masjid Agung Keraton Plered, menandai kedudukannya yang tidak hanya penting secara politik, tetapi juga simbolik dalam ingatan istana.
Dengan naiknya Pakubuwana I sebagai raja Mataram Kartasura pada tahun 1704, darah Kajoran yang pada abad ketujuh belas dilekatkan dengan stigma oposisi, pembangkangan, dan perlawanan moral terhadap absolutisme Mataram justru berbalik menjadi sumber legitimasi bagi raja baru. Dari titik inilah Wangsa Kajoran melahirkan dua poros utama dalam sejarah Jawa, yakni poros kekuasaan politik melalui garis raja raja Surakarta serta poros kebudayaan keraton melalui trah pujangga yang mencapai puncaknya pada figur Ronggowarsito.
Sejarah ini memperlihatkan satu pola yang tegas. Ponorogo runtuh sebagai negara teritorial, tetapi bangkit sebagai rahim genealogis. Wangsa Kajoran mungkin kalah secara politik pada satu fase sejarah, tetapi menang secara jangka panjang. Ia bertahan bukan dengan pasukan, melainkan dengan darah, perkawinan, spiritualitas, dan kemampuan membaca zaman. Dalam sejarah Jawa, kekuasaan sejati tidak selalu bersemayam di singgasana, melainkan mengalir senyap melalui silsilah dan ingatan kolektif lintas abad.

Catatan Akhir: Dari Negara Dakwah ke Rahim Genealogis Jawa
Sejarah awal Kadipaten Ponorogo menegaskan satu pelajaran mendasar dalam politik Jawa. Negara ini tidak runtuh karena kekalahan militer ataupun tekanan eksternal, melainkan akibat pergeseran watak kekuasaan dari disiplin pendiri menuju kelonggaran pada masa pewaris. Batoro Katong membangun Ponorogo sebagai negara dakwah dengan kontrol kekuasaan yang kuat, struktur pemerintahan yang tegas, serta legitimasi spiritual yang berakar pada otoritas wali. Panembahan Agung mewarisi bangunan negara tersebut, tetapi mengalihkan pusat gravitasinya dari penguasaan teritorial menuju penguatan nasab dan jaringan spiritual. Negara tetap berdiri secara formal, namun perlahan kehilangan daya kendali politiknya.
Dalam situasi demikian, stabilitas Ponorogo tidak lagi bertumpu pada institusi, melainkan pada figur perantara seperti Suramenggala, sosok penjaga senyap yang menahan keretakan dari dalam. Ketika negara bergantung pada loyalitas personal, bukan pada sistem pemerintahan yang kokoh, kemunduran menjadi proses yang nyaris tak terhindarkan. Namun dari surutnya kekuasaan teritorial inilah Ponorogo justru melahirkan keberhasilan lain yang lebih tahan lama. Ia tidak lagi tampil sebagai pusat politik, tetapi hidup sebagai rahim genealogis elite Jawa.
Keragaman versi mengenai asal usul Panembahan Agung sebagai putra cucu atau menantu Batoro Katong mencerminkan dinamika konstruksi legitimasi dalam tradisi babad dan silsilah bangsawan Jawa. Meski demikian hampir seluruh tradisi sepakat menempatkan Batoro Katong sebagai leluhur utama Wangsa Kajoran. Melalui garis keturunan inilah jaringan darah perkawinan politik dan otoritas spiritual Ponorogo mengalir menuju Pajang Mataram Islam hingga Surakarta sehingga membentuk poros kekuasaan dan kebudayaan Jawa lintas abad.
Jejak sejarah tersebut juga terpatri dalam lanskap memorial Ponorogo. Panembahan Agung dimakamkan di kompleks pemakaman Batoro Katong di kawasan Setono, tepat di sebelah kanan Gedong Batoro Katong, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Makam ini menjadi penanda kesinambungan sejarah sekaligus pengingat bahwa perjalanan kekuasaan Ponorogo tidak hanya hidup dalam naskah dan silsilah, tetapi juga dalam ruang ingatan kolektif masyarakat yang terus merawat warisan para pendirinya.
*konten ini dibuat dengan bantuan AI










